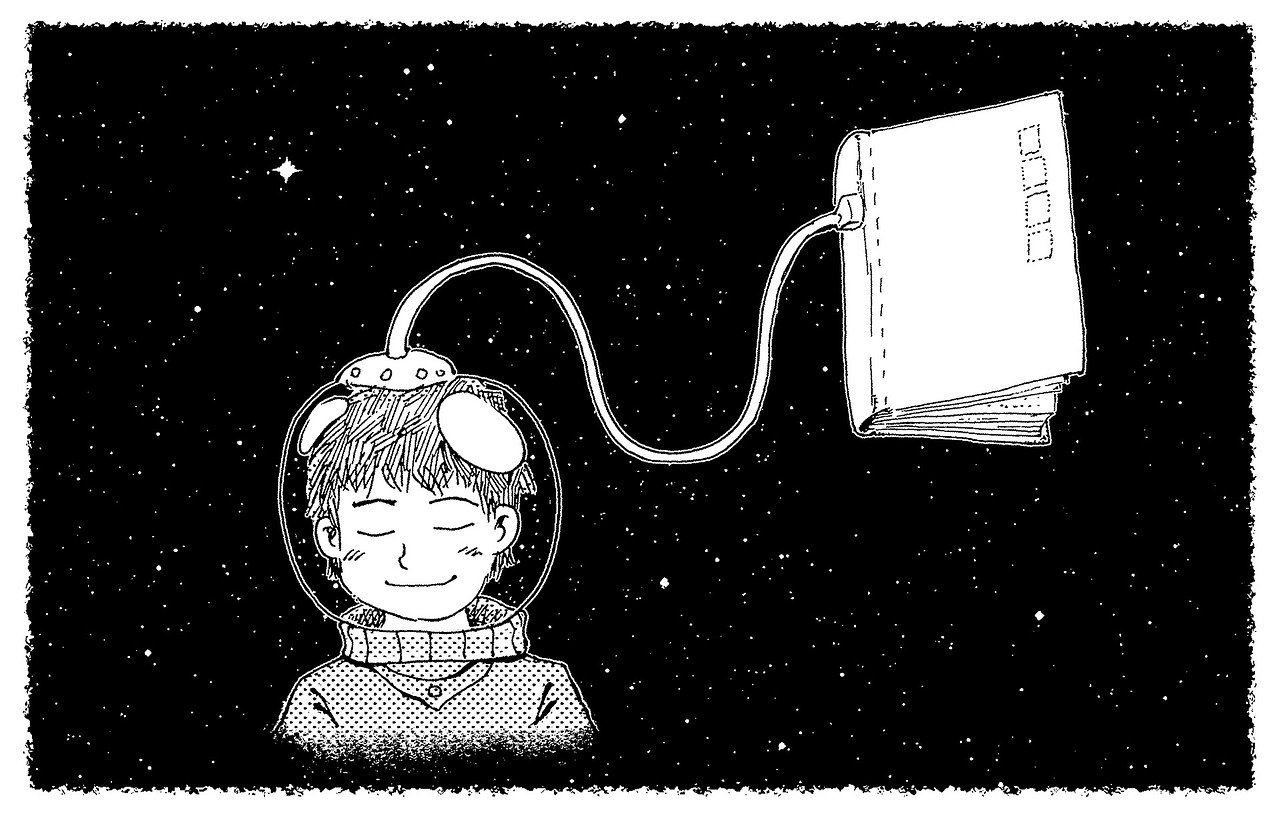SASTRA MASUK KURIKULUM TANPA KANON
Esai Ahmadun Yosi Herfanda, pemred Litera.
____________________________________________________________________
Sastra masuk kurikulum. Ini tentu kabar gembira bagi sastrawan – baik penyair, cerpenis, maupun novelis — yang merindukan karyanya dinikmati dan diapresiasi oleh siswa. Tetapi, itu juga sekaligus “jebakan” bagi sastrawan yang karyanya tidak segmented untuk siswa. Kegembiraan itu bisa berubah menjadi kegaduhan yang kurang produktif.
___________
Ilustrasi diambil dari www.google.co.id
_______________
Seperti kita lihat, ketika daftar buku yang harus masuk kurikulum (buku kanon) diumumkan, banyak kalangan, terutama sastrawan, yang keberatan dan menyampaikan protes melalui berbagai media. Mereka menganggap pemilihan buku-buku kanon, terutama buku-buku untuk siswa SMP dan SMA, ada yang tidak sesuai dengan segmen pembaca. Sehingga, daftar buku kanon yang sudah diumumkan oleh Kemendikbudristek pun ditarik kembali.
Pada laman Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (buku.kemdikbud.go.id), halaman Daftra Rekomendasi Buku, pada tanggal 12-13 Juni 2024, kita hanya bisa melihat buku-buku untuk siswa SD yang sudah lolos kurasi, dan masih ada beberapa buku yang tidak bisa diakses. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA tidak bisa dilihat sama sekali, karena buku-buku itu sedang ditinjau kembali.
Jika menyimak kegaduhan yang terjadi, kita curiga bahwa sebagian tim reviewer kurang teliti dalam membaca buku-buku yang dikanonkan, dan terkesan kurang mengetahui peta perkembangan sastra Indonesia. Ada sastrawan yang masih hidup dianggap sudah mati. Ada novel dewasa yang direkomendasi untuk siswa SMA, yang masih remaja. Ada sejumlah sastrawan, yang dipercaya menjadi kurator, merekomendasi karya sendiri.
Jadinya, kanonisasi buku sastra untuk masuk kurikulum cukup banyak menyimpan masalah dan bahkan cenderung menyesatkan. Bagaimana tidak, presiden penyair Sutardji Calzoum Bachri, yang nasih segar bugar, dianggap sudah meninggal. Ini terjadi, karena kurator yang bertugas membaca biografi Sutardji kurang teliti, atau kurang mengikuti perkembangan. Mestinya, kekonyolan-kekonyolan semacam itu tidak perlu terjadi.
Berisiko
Memasukkan sastra ke dalam kurikulum tentu sangat baik, jika dilakukan secara benar, dan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan apresiasi sastra siswa. Sehingga, diharapkan, siswa memiliki apresiasi sastra yang tinggi dan setelah lulus nanti menjadi warga negara yang bisa menghargai karya sastra, serta memiliki karakter yang unggul dan siap bersaing di era global. Pengajaran sastra masih merupakan bagian penting dari pendidikan karakter.
Apakah karena itu perlu dilakukan politik kanonisasi? Hanya karya sastra yang dianggap sebagai kanon saja yang bisa masuk kurikulum, sementara di luar daftar buku kanon itu masih sangat banyak karya sastra unggulan? Upaya kanonisasi karya sastra saja sudah menimbulkan persoalan yang pelik, dan akan lebih pelik lagi jika dikaitkan dengan kurikulum sekolah. Persoalan pertama ada pada proses kanonisasi, yang dilakukan beberapa kurator dengan bantuan reviewer. Sementara, para sastrawan dan publik sastra hanya menikmati kegaduhannya. Sejumlah karya sastra dipilih dan direkomendasi untuk masuk kurikulum. Proses ini bisa menimbulkan persoalan jika pemilihan terkesan kurang objektif. Apalagi kalau yang memilih dianggap kurang kredibel.
Persoalan selanjutnya akan muncul ketika karya sastra yang menjadi kanon itu wajib dibaca siswa karena ada dalam mata pelajaran sekolah, atau masuk kurikulum. Pertama, kurikulum semacam itu akan membatasi kemerdekaan siswa untuk membaca karya-karya sastra lain yang bertebaran di perpustakaan sekolah, toko-toko buku, dan media-media sosialisasi karya sastra. Prinsip “merdeka belajar” bisa menjadi “tidak merdeka belajar”. Para siswa akan merasa “cukup” mengetahui isi buku karya sastra yang diajarkan oleh gurunya saja.
Persoalan kedua, kanonisasi buku sastra, yang terbatas dan tidak memasukkan karya-karya sastra unggulan dari para sastrawan yang bukan kanon, akan menimbulkan kecurigaan yang dapat memancing kegaduhan. Dan, kegaduhan itu bisa berkembang secara liar, mengingat karakter media sosial yang cenderung anarkis. Anarkisme ini, jika terus berkembang dan meluas, bisa menggilas “daftar resmi” buku sastra yang telah direkomendasi untuk masuk kurikulum itu. Akibatnya, program berbiaya mahal yang menimbulkan kegaduhan itu harus ditarik kembali. Inilah risiko yang harus dihadapi oleh Kemendikbudristek, akibat gagalnya politik kanonisasi sastra itu.
Tanpa kanon
Mungkin akan lebih baik jika tanpa “politik kanonisasi”. Karya sastra tetap masuk kurikulum tapi tanpa kanonisasi. Para guru bahasa cukup didorong untuk memanfaatkan karya sastra sebagai salah satu bahan ajar bahasa, seperti bahan ajar tata kalimat dan gaya bahasa. Sedangkan guru-guru ilmu sosial, sejarah, dan agama, juga didorong untuk memanfaatkan karya sastra yang sesuai sebagai salah satu bahan ajar. Jadi, dalam kurikulum cukuplah disebutkan bahwa salah satu sumber ajar adalah karya sastra. Dan, sumber utamanya tetaplah buku-buku paket bidang studi masing-masing. Biarlah para guru, dengan perasaan dan pikiran merdeka, memilih sendiri karya sastra unggulan untuk menambah bahan ajar di kelasnya. Banyak di antara mereka yang sudah pintar, berpendidikan pasca sarjana, bahkan doktor. Ada beberapa guru bahasa yang juga sastrawan ternama.
Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot menyusun daftar buku kanon untuk kurikulum. Biarlah kanonisasi itu berproses secara alami di masyarakat, terutama di tengah-tengah publik sastra. Kemendikbudristek cukuplah memperbanyak penerbitan buku-buku karya sastra unggulan untuk disebar ke sekolah-sekolah, untuk mengisi perpustakaan sekolah, dan sebagian buku itu dipajang secara bergantian di rak-rak buku ruang kelas, agar para siswa merasa dekat dengan buku-buku sastra. Dan, para guru bisa memulai pelajaran secara dialogis dengan sedikit membahas buku sastra yang sesuai dan ada di ruang kelas masing-masing. Jadi, daripada mebuat kanonisasi yang menyulut kegaduhan, lebih baik dana dipakai untuk memperbanyak penerbitan buku sastra.
Kreativitas guru
Dari dulu hingga sekarang, dari zaman bahulea sampai zaman milenial, inti persoalan pengajaran sastra tetap sama: kurangnya niat baik dan kreativitas guru dalam mengajarkan apresiasi sastra. Guru yang kreatif, yang mencintai karya sastra, dan memiliki niat baik untuk mengajak siswa sesekali menyelami karya sastra serta memahami nilai-nilai positifnya, akan menemukan jalan untuk itu. Kurikulum hanya merupakan media bantu untuk menemukan jalan dan mengarahkan sang guru dan para siswa agar tidak tersesat.
Diperlukan kreativitas guru dalam menyiasati keterbatasan waktu dan minat sastra siswa yang umumnya rendah. Guru yang kreatif, baik guru bahasa maupun guru yang lain, akan selalu menemukan cara yang menarik dan pas untuk mendekatkan siswa dengan karya sastra. Selain merujuk pada karya-karya sastra yang ada dalam buku teks, guru juga bisa mencontohkan karya-karya sastra yang ada di perpustakaan sekolah, dan karya-karya sastra unggulan yang beredar di masyarakat.
Dengan cara begitu saja, siswa sudah kehabisan waktu untuk melayani minat dan kewajiban bacanya. Beban pelajaran siswa sudah sangat berat. Janganlah diperberat lagi dengan “keinginan orang tua” untuk “menenggelamkan” siswa ke dalam karya-karya sastra yang kurang perlu mereka baca. Berilah kemerdekaan pada siswa untuk memilih bacaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bukankan ini pinsip “merdeka belajar” yang sesungguhnya? Belajar dengan merdeka, membangun impian masa depan, tanpa politik kanonisasi sastra. @
Esai ini telah ditayang di Koran Tempo, 16 Juni 2024, pada halaman “Teroka”.